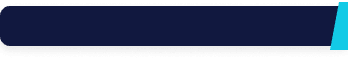Kearifan Bahari dalam Agama

Kearifan Bahari dalam Agama
A
A
A
Suasana pada acara diskusi dan bedah buku Agama dalam Kearifan Bahari karya Radhar Panca Dahana. Acara ini merupakan seri lanjutan dari bedah buku dalam rangka peringatan hari ulang tahun penulis Radhar Panca Dahana.
Hal inilah yang mengemuka dalam diskusi buku Radhar Panca Dahana berjudul Agama dalam Kearifan Bahari di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pekan lalu.
Moderator diskusi adalah Saifur Rohman dengan para pembicara guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar FaridMasudi, tokohagamaBuddhayang menjabat Ketua Umum Niciren Sosyu Indonesia (NSI) Suhadi Sendjaja, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama (Kemenag) I Ketut Widnya.
Masdar Masudi berpendapat, buku Radhar sangat relevan dengan kondisi keberagaman di Tanah Air, khususnya keberagaman Islam yang sedemikian rupa pada perkembangan terakhir ini. Buku Radhar lebih substantif sesuai dengan keberagaman Nusantara ketimbang fokus pada masalah lahiriah. Saat ini, katanya, semua yang terjadi dalam kehidupan agama di Tanah Air sudah berlebihan, tidak seimbang dan tidak proporsional. Negara dalam hal ini dianggap telah banyak melewati batas dalam mengatur kehidupan beragama.
Akibatnya, hierarki otoritas menjadi kacau, dan negara pun menjadi pihak segala-galanya. “Ketika negara bersinggungan dengan agama, negara hanya boleh mengambil pesan-pesan nondiskriminatif terhadap wajah yang ada di dalamnya berdasarkan suku, keyakinan, agama, primordial, dan lain-lain,” urainya.
Bisa terjadi kondisi yang begitu kacau jika lembaga negara yang inklusif masuk ke dalam wilayah beragama pribadi yang eksklusif. Dalam hal ini, negara akan sangat baik jika dibatasi gerak dan langkahnya. Negara, lanjut dia, tetap bisa hadir, tapi tidak boleh campur tangan jika individu bisa melakukannya sendiri atau mandiri. Suhadi pun senada dengan Masdar.
Dia menegaskan, NSIsangat menyayangkan banyak tokoh agama dan umatnya tidak menempatkan Tuhan dan agama pada tempat yang tidak proporsional. Baginya, agama bahari harus diletakkan dalam pemikiran kearifankearifan lokal. Agama harus diletakkan dalam posisi yang berbasis tradisi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti bola salju yang semakin menggelinding semakin besar dan banyak salju yang diserapnya.
“Radhar bisa menerawang lebih dalam, yakni ada kekuatan lain, yaitu modal atau kapital yang dilihat sebagai hal dahsyat. Apa saja bisa dibeli. Termasuk bentrokan, kekerasan, kekacauan, kerusuhan,” ujarnya. Adapun Azyumardi Azra, menggarisbawahi berbagai kekerasan berlatar agama seperti ISIS, terorisme, radikalisme, atau gerakan keras lain sebagai hal yang tidak bisa memiliki tempat di Tanah Air. Mengapa?
Dalam hal ini dia menceritakan tentang sejarah negara Islam di Nusantara yang sejak awal telah dipusatkan di pelabuhan. Sehingga Islam bahari atau Indonesia bersifat kosmopolit atau mendunia. Karena pelabuhan, Islam bahari pun menjadi agama yang terbuka, inklusif, cair, dan akomodatif. Karakter Islam di Tanah Air inilah yang dia tegaskan tidak akan ditemui di negara manapun di luar negeri.
Dia mencontohkan Islam di Timur Tengah yang hidup di padang pasir yang menyebabkan watak budaya cenderung keras, didominasi lelaki, dan tidak ada ruang untuk toleransi dan kerap menjadi pusat konflik. Sebaliknya, watak Islam Tanah Air adalah organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang memegang jalan tengah, yakni toleran dan moderat. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.
“Kita perlu menghidupkan dan memperkuat kembali Islam bahari yang inklusif dan kosmopolit itu,” katanya. Menghidupkan kembali Islam bahari yang inklusif dan kosmopolit akan menempatkan agama dalam tempat yang proporsional sebagaimana mestinya. Sementara itu, Franz Magnis- Suseno mengutarakan kekhawatiran akan modernitas yang dinilainya telah banyak merenggut jati diri manusia.
Modernitas menjadi sebuah dimensi baru yang tak terelakkan karena terikat dengan perkembangan teknologi, yang memang mau tak mau dibutuhkan. Modernitas ini juga yang telah mengacaukan kehidupan antara sesama umat manusia di Tanah Air, yang sebetulnya sedari zaman dulu tak pernah ada pergolakan dan selalu hidup tenang dan damai dalam keberagaman.
“Agama di Indonesia itu sebetulnya beruntung. Mengapa? Karena kebangkitan agama (Islam) menjadi bagian pendukung kebangkitan nasional. Itu adalah suatu proses yang baik. Karena itu mainstream agama kita adalah NKRI,” paparnya. Saat ini banyak pemeluk agama yang dianggap tak lagi bisa menolak kekerasan atau menerima begitu saja. Dan kemampuan untuk menerima orang lain dalam keberlainan atau perbedaan juga melemah.
Padahal, ini adalah toleransi Indonesia yang sangat tradisional, yang sudah terbentuk sejak dulu kala. Semua ini disebabkan bukan karena kepicikan agama, atau agamanya yang salah. Tapi karena kompetisi yang tidak sehat, yang diluncurkan modernitas tersebut. “Saya ingin memperkuat keseimbangan dengan menghormati, yakni menerima yang ada, dan menghormati alam, menghormati yang berbeda. Karena di dalam tradisi Indonesia hormat itu ada,” ujarnya.
Kemudian I Ketut Widnya menyatakan, kebudayaan bahari itu semestinya meneguhkan rakyat Indonesia untuk memelihara alam dan keseimbangan. “Agama sekarang terkotak-kotak. Kalau dalam kotak kecil lebih seru lagi, menjelekkan agama lain,” tegasnya. Lalu sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi semakin lama semakin menghilang membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan beragama.
Susi susanti
Hal inilah yang mengemuka dalam diskusi buku Radhar Panca Dahana berjudul Agama dalam Kearifan Bahari di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pekan lalu.
Moderator diskusi adalah Saifur Rohman dengan para pembicara guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar FaridMasudi, tokohagamaBuddhayang menjabat Ketua Umum Niciren Sosyu Indonesia (NSI) Suhadi Sendjaja, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama (Kemenag) I Ketut Widnya.
Masdar Masudi berpendapat, buku Radhar sangat relevan dengan kondisi keberagaman di Tanah Air, khususnya keberagaman Islam yang sedemikian rupa pada perkembangan terakhir ini. Buku Radhar lebih substantif sesuai dengan keberagaman Nusantara ketimbang fokus pada masalah lahiriah. Saat ini, katanya, semua yang terjadi dalam kehidupan agama di Tanah Air sudah berlebihan, tidak seimbang dan tidak proporsional. Negara dalam hal ini dianggap telah banyak melewati batas dalam mengatur kehidupan beragama.
Akibatnya, hierarki otoritas menjadi kacau, dan negara pun menjadi pihak segala-galanya. “Ketika negara bersinggungan dengan agama, negara hanya boleh mengambil pesan-pesan nondiskriminatif terhadap wajah yang ada di dalamnya berdasarkan suku, keyakinan, agama, primordial, dan lain-lain,” urainya.
Bisa terjadi kondisi yang begitu kacau jika lembaga negara yang inklusif masuk ke dalam wilayah beragama pribadi yang eksklusif. Dalam hal ini, negara akan sangat baik jika dibatasi gerak dan langkahnya. Negara, lanjut dia, tetap bisa hadir, tapi tidak boleh campur tangan jika individu bisa melakukannya sendiri atau mandiri. Suhadi pun senada dengan Masdar.
Dia menegaskan, NSIsangat menyayangkan banyak tokoh agama dan umatnya tidak menempatkan Tuhan dan agama pada tempat yang tidak proporsional. Baginya, agama bahari harus diletakkan dalam pemikiran kearifankearifan lokal. Agama harus diletakkan dalam posisi yang berbasis tradisi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti bola salju yang semakin menggelinding semakin besar dan banyak salju yang diserapnya.
“Radhar bisa menerawang lebih dalam, yakni ada kekuatan lain, yaitu modal atau kapital yang dilihat sebagai hal dahsyat. Apa saja bisa dibeli. Termasuk bentrokan, kekerasan, kekacauan, kerusuhan,” ujarnya. Adapun Azyumardi Azra, menggarisbawahi berbagai kekerasan berlatar agama seperti ISIS, terorisme, radikalisme, atau gerakan keras lain sebagai hal yang tidak bisa memiliki tempat di Tanah Air. Mengapa?
Dalam hal ini dia menceritakan tentang sejarah negara Islam di Nusantara yang sejak awal telah dipusatkan di pelabuhan. Sehingga Islam bahari atau Indonesia bersifat kosmopolit atau mendunia. Karena pelabuhan, Islam bahari pun menjadi agama yang terbuka, inklusif, cair, dan akomodatif. Karakter Islam di Tanah Air inilah yang dia tegaskan tidak akan ditemui di negara manapun di luar negeri.
Dia mencontohkan Islam di Timur Tengah yang hidup di padang pasir yang menyebabkan watak budaya cenderung keras, didominasi lelaki, dan tidak ada ruang untuk toleransi dan kerap menjadi pusat konflik. Sebaliknya, watak Islam Tanah Air adalah organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang memegang jalan tengah, yakni toleran dan moderat. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.
“Kita perlu menghidupkan dan memperkuat kembali Islam bahari yang inklusif dan kosmopolit itu,” katanya. Menghidupkan kembali Islam bahari yang inklusif dan kosmopolit akan menempatkan agama dalam tempat yang proporsional sebagaimana mestinya. Sementara itu, Franz Magnis- Suseno mengutarakan kekhawatiran akan modernitas yang dinilainya telah banyak merenggut jati diri manusia.
Modernitas menjadi sebuah dimensi baru yang tak terelakkan karena terikat dengan perkembangan teknologi, yang memang mau tak mau dibutuhkan. Modernitas ini juga yang telah mengacaukan kehidupan antara sesama umat manusia di Tanah Air, yang sebetulnya sedari zaman dulu tak pernah ada pergolakan dan selalu hidup tenang dan damai dalam keberagaman.
“Agama di Indonesia itu sebetulnya beruntung. Mengapa? Karena kebangkitan agama (Islam) menjadi bagian pendukung kebangkitan nasional. Itu adalah suatu proses yang baik. Karena itu mainstream agama kita adalah NKRI,” paparnya. Saat ini banyak pemeluk agama yang dianggap tak lagi bisa menolak kekerasan atau menerima begitu saja. Dan kemampuan untuk menerima orang lain dalam keberlainan atau perbedaan juga melemah.
Padahal, ini adalah toleransi Indonesia yang sangat tradisional, yang sudah terbentuk sejak dulu kala. Semua ini disebabkan bukan karena kepicikan agama, atau agamanya yang salah. Tapi karena kompetisi yang tidak sehat, yang diluncurkan modernitas tersebut. “Saya ingin memperkuat keseimbangan dengan menghormati, yakni menerima yang ada, dan menghormati alam, menghormati yang berbeda. Karena di dalam tradisi Indonesia hormat itu ada,” ujarnya.
Kemudian I Ketut Widnya menyatakan, kebudayaan bahari itu semestinya meneguhkan rakyat Indonesia untuk memelihara alam dan keseimbangan. “Agama sekarang terkotak-kotak. Kalau dalam kotak kecil lebih seru lagi, menjelekkan agama lain,” tegasnya. Lalu sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi semakin lama semakin menghilang membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan beragama.
Susi susanti
(ars)